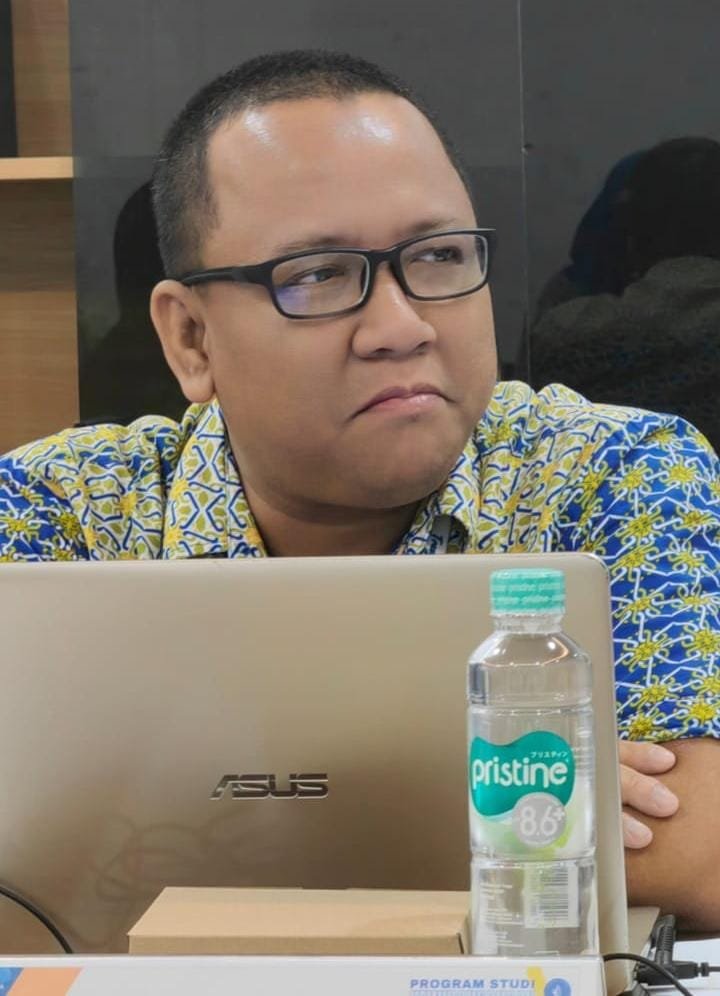Oleh: Moh. Ikhsan Kurnia, S.Sos., MBA.
Dalam diskursus pembangunan ekonomi Asia Tenggara, narasi tentang negara-negara seperti Singapura, Malaysia, atau bahkan Vietnam seringkali memenuhi lembaran analisis pertumbuhan. Namun, terdapat pelajaran yang sama pentingnya dari negara-negara yang tidak berhasil mengorkestrasi perkembangan kewirausahaan mereka: Laos dan Myanmar. Alih-alih menjadi lokomotif pemberdayaan ekonomi rakyat, sektor UMKM di dua negara ini cenderung mengalami stagnasi, bahkan regresi dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini patut kita telaah bukan dalam semangat schadenfreude, tetapi sebagai cautionary tale yang mencerminkan jebakan struktural dan institusional yang juga mengintai Indonesia.
Laos, sebuah negara landlocked yang secara geografis dikepung oleh negara-negara bertumbuh pesat, sesungguhnya memiliki potensi untuk menjadi land-linked economy—yakni model pembangunan yang mengandalkan konektivitas regional dan logistik sebagai fondasi ekonomi. Namun, ketergantungan berlebih pada bantuan luar negeri serta lemahnya institutional capacity membuat program kewirausahaan hanya berhenti pada level programmatic tokenism, bukan pada ekosistem yang benar-benar tumbuh secara organik. Menurut laporan Asian Development Bank (ADB, 2020), lebih dari 85% pelaku UMKM di Laos masih beroperasi secara informal tanpa akses terhadap pembiayaan produktif, pelatihan manajerial, atau integrasi pasar regional.
Myanmar memiliki ironi yang lebih kompleks. Negara ini pernah menunjukkan geliat awal kewirausahaan pasca-reformasi 2011, ketika liberalisasi ekonomi mulai dibuka dan komunitas internasional menaruh harapan akan transformasi sosial-ekonomi. Namun, harapan itu terhenti akibat kembalinya instabilitas politik yang akut, termasuk kudeta militer tahun 2021. Kewirausahaan yang seharusnya menjadi lokomotif inclusive growth justru lumpuh akibat kepastian hukum yang nihil, represi terhadap hak milik, serta terputusnya supply chain internasional. United Nations ESCAP (2022) mencatat bahwa lebih dari 60% pelaku UMKM di Myanmar kehilangan akses pasar dan modal kerja hanya dalam kurun 12 bulan setelah kudeta.
Dari dua kasus ini, ada pola kegagalan yang dapat dikenali: pertama, ketiadaan governance yang stabil; kedua, lemahnya kapasitas lembaga penggerak UMKM; ketiga, absennya entrepreneurial literacy di kalangan masyarakat luas; dan keempat, ekosistem regulasi yang lebih banyak menciptakan friksi ketimbang insentif. Dalam terminologi Douglas North (1990), kegagalan ekonomi bukan semata karena keterbatasan sumber daya, melainkan akibat dari “institusi yang salah urus” (institutional misalignment), yang menjadikan aktivitas produktif sebagai pilihan rasional yang tidak menarik bagi warga negara.
Mengapa hal ini relevan bagi Indonesia? Karena kita pun tidak imun terhadap dinamika serupa. Di tengah geliat semangat kewirausahaan nasional, masih ada tantangan besar berupa tumpang tindih regulasi, disparitas kapasitas antar daerah, serta rendahnya efektivitas lembaga pendamping UMKM. Lembaga seperti PLUT-KUMKM, walau secara konsep mirip dengan Negosyo Centers di Filipina, masih belum memiliki penetrasi yang merata secara nasional. Sebuah studi dari LPEM FEB UI (2022) menunjukkan bahwa hanya 28% UMKM di Indonesia yang pernah mendapatkan pelatihan bisnis formal, dan kurang dari 12% yang memiliki business model canvas yang tervalidasi pasar.
Lebih dari itu, Indonesia juga harus mewaspadai gejala program fatigue, di mana program-program kewirausahaan hanya menjadi proyek jangka pendek tanpa kesinambungan atau akuntabilitas. Seperti halnya di Laos, terlalu banyak program inkubasi dan pelatihan yang tidak diikuti dengan strategi exit yang berkelanjutan. Dalam bahasa Pierre Bourdieu, terjadi semacam symbolic violence terhadap UMKM, di mana mereka diperlakukan sebagai objek belas kasih pembangunan, bukan sebagai subjek ekonomi yang berdaulat.
Pelajaran dari Myanmar juga penting, khususnya tentang pentingnya political predictability. Tanpa jaminan stabilitas dan rule of law, maka kewirausahaan hanya akan berkembang dalam shadow economy, yang pada akhirnya memperparah ketimpangan sosial dan memperbesar ruang rente.
Untuk itu, Indonesia perlu melampaui pendekatan normatif yang menekankan semata pada “membuka akses permodalan”. Yang lebih mendesak adalah membangun entrepreneurial ecosystem berbasis tata kelola adaptif—dengan integrasi antara pendidikan kewirausahaan sejak dini, reformasi regulasi yang menyederhanakan perizinan, serta digitalisasi sistem pendampingan dan pelaporan.
Studi dari World Bank (2021) menyatakan bahwa ekosistem kewirausahaan yang berhasil adalah yang mampu membangun sinergi antara empat aktor utama: pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan komunitas wirausaha itu sendiri. Di sini, peran negara bukan sekadar sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai orchestrator of trust—yakni menciptakan ruang di mana risiko bisa dikelola bersama dan keberhasilan bisa direplikasi secara sistematis.
Sebagai bangsa dengan populasi produktif terbesar keempat di dunia, Indonesia sedang berada di simpang jalan historis. Kita bisa memilih untuk menjadi bangsa wirausaha yang tahan banting—dengan entrepreneurial resilience dan institutional coherence—atau terjebak dalam jebakan “Laosifikasi” dan “Myanmarisasi” ekonomi rakyat, di mana semangat kewirausahaan direduksi menjadi retorika tanpa struktur.
Menatap ke depan, kita membutuhkan keberanian untuk membongkar cara-cara lama dan membangun paradigma baru kewirausahaan yang bukan hanya bertumpu pada logika pasar, tetapi juga etika pembangunan. Dengan itu, kewirausahaan bukan sekadar menjadi sarana mencari nafkah, tetapi menjadi proyek kultural bangsa dalam membangun martabat, solidaritas, dan kemandirian.
*Penulis adalah Dosen Kewirausahaan Universitas BTH & Direktur Kemitraan Perkumpulan Program Studi Kewirausahaan Indonesia (APSKI); Pemerhati Kewirausahaan Asia Tenggara.