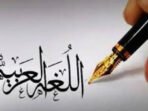Oleh:
Muhamad Tamamul Iman, M.Phil
Dosen Filsafat Fakultas Ushuluddin
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Pernahkah Anda merasa hidup di zaman yang serba ditonton?
Di mana setiap langkah, tawa, bahkan kesedihan, seakan punya nilai hanya ketika direkam dan dibagikan? Kita hidup di masa ketika kamera bukan lagi sekadar alat dokumentasi, tetapi jendela menuju pengakuan. Maka tak heran, banyak orang kini rela melakukan apa saja demi konten — dari yang konyol, nekat, hingga berbahaya.
Fenomena ini bukan sekadar soal hiburan digital. Ia mencerminkan kegelisahan yang lebih dalam: tentang makna kebahagiaan, kebebasan, dan eksistensi manusia di era digital. Banyak orang merasa bebas ketika bisa menampilkan diri di media sosial, padahal tanpa sadar justru sedang dikendalikan oleh algoritma yang menilai: siapa yang pantas dilihat, siapa yang layak viral.
Manusia, sejak awal, selalu mengejar kebahagiaan. Dari kecil, kita ditanya: “Mau jadi apa nanti?” Jawaban pun beragam—dokter, artis, pejabat, bahkan presiden. Tapi, bila ditanya lebih jauh: “Setelah semua itu tercapai, lalu apa?” banyak yang terdiam. Sebab, ternyata kebahagiaan yang dikejar sering kali berhenti pada pencapaian luar, bukan kedalaman batin.
Kini, di era digital, pencarian kebahagiaan itu mengambil bentuk baru: fenomena “demi konten”. Demi tampil menarik di media sosial, banyak orang rela melakukan hal-hal ekstrem, bahkan berisiko pada diri dan orang lain. Mulai dari aksi berbahaya di jalanan, merusak alam, hingga eksploitasi tubuh—semuanya demi satu tujuan: viral, diakui, dan eksis.
Paradoks Kebebasan Digital
Teknologi digital, yang awalnya menjanjikan ruang kebebasan, justru menghadirkan paradoks baru. Kita bisa berkata apa saja, namun takut kehilangan like. Kita bisa mengekspresikan diri, tapi cemas tak mendapat perhatian. Dunia digital menjanjikan otonomi, tapi diam-diam mengikat kita dalam penilaian sosial tanpa henti.
Jean Baudrillard menyebutnya sebagai hiperrealitas—keadaan ketika dunia maya lebih nyata dari kenyataan itu sendiri (Baudrillard, 1994). Di ruang semu ini, manusia tidak lagi hidup untuk dirinya, melainkan untuk tampil.
Tak heran, demi sepotong video viral, ada yang nekat berpose di rel kereta, beraksi di jalan raya, atau melakukan prank yang berujung petaka. Semua demi satu hal: diakui, dilihat, dianggap ada.
Inilah paradoks kebebasan digital: manusia tampak bebas mengekspresikan diri, padahal sesungguhnya terperangkap dalam logika popularitas. Kebebasan berekspresi menjelma menjadi tekanan untuk tampil sempurna. Segalanya diukur oleh like, view, dan subscriber.
Fenomena ini telah melahirkan banyak tragedi. Seorang remaja di Sukabumi tewas tertabrak truk saat membuat konten; ada pula yang nekat menantang maut di jembatan atau membakar hutan hanya demi sensasi. Apa sesungguhnya yang dicari? Jawabannya sederhana: pengakuan.
Padahal, kata Leon Festinger, manusia memang memiliki dorongan untuk menilai dirinya lewat perbandingan dengan orang lain (Festinger, 1954). Masalahnya, ketika ukuran kebahagiaan ditentukan oleh jumlah viewer, kita akan terus hidup dalam kecemasan untuk mempertahankan eksistensi yang rapuh.
Eksistensi yang Hilang di Balik Layar
Fenomena “demi konten” adalah potret eksistensi yang kehilangan arah.
Karl Jaspers, filsuf eksistensialis Jerman, menegaskan bahwa manusia baru sungguh ada ketika ia sadar akan kebebasannya—yakni kemampuan untuk memilih dan memberi makna atas hidupnya sendiri (Jaspers, 1970).
Namun di dunia digital, kebebasan itu berubah menjadi semu: kita memilih untuk meniru, bertindak karena tren, bukan karena kesadaran diri.
Eksistensi, bagi Jaspers, tidak bisa diobjektifikasi. Ia bukan tontonan, melainkan kesadaran yang lahir dari refleksi dan komunikasi yang autentik. Tapi kini, “aku” justru menjadi objek tontonan publik. Hidup diukur dari seberapa banyak perhatian yang didapat, bukan dari sejauh mana seseorang memahami dirinya.
Maka, yang terjadi adalah ironi: kita bebas, tapi terperangkap. Kita ingin menunjukkan diri, tetapi kehilangan jati diri itu sendiri.
Bahagia yang Menenangkan
Jika kebebasan digital membuat kita gelisah, mungkin kita perlu menengok kembali kebijaksanaan lama. Filsafat Stoa, melalui Epiktetus, mengajarkan ataraxia—ketenangan batin yang muncul ketika seseorang mampu mengendalikan hal-hal dalam kuasanya dan menerima hal-hal di luar kendalinya (Epictetus, Enchiridion).
Artinya, kebahagiaan bukanlah hasil dari perhatian orang lain, melainkan dari penguasaan diri.
Sayangnya, manusia digital lebih sering dikuasai oleh keinginan untuk terlihat, bukan keinginan untuk memahami. Padahal, penderitaan sering kali bukan datang dari apa yang terjadi, melainkan dari cara kita memaknainya.
Menemukan Kembali Diri
Di tengah hiruk pikuk dunia maya, mungkin langkah paling revolusioner bukanlah tampil lebih banyak, tetapi berani untuk berhenti sejenak. Menikmati keheningan, memeriksa diri, dan menanyakan ulang: apakah aku sungguh bahagia, atau hanya tampak bahagia di layar?
Karl Jaspers pernah menulis bahwa eksistensi sejati adalah proses menjadi diri sendiri dalam kebebasan. Artinya, manusia merdeka bukan ketika ia bisa melakukan apa pun, melainkan ketika ia mampu menolak apa yang tidak perlu ia lakukan.
Mungkin di era di mana semua orang ingin dilihat, sikap paling eksistensial justru adalah berani untuk tidak tampil.
Sebab, hanya dalam kesunyian, manusia bisa mendengar dirinya sendiri — dan menemukan makna kebebasan yang sejati.@Juanda